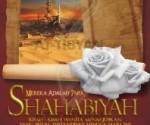Ibn Taimiyah, Ulama Mujahid yang Pemaaf
Oleh Muhamad Sabrul Murajjab*
Terorisme, kini kembali menjadi buah bibir. Umat Islam lagi-lagi dijadikan santapan empuk, opini yang berkembang semakin liar! Di Indonesia, dunia pesantren disorot dengan pandangan tajam penuh kecurigaan. Kegiatan dakwah di bulan Ramadan yang suci bahkan sempat terdengar santer akan diawasi aparat. Beberapa nama tokoh pembaharu Islam masa lalu juga kembali disebut sebut sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dibalik penyebaran “fundamentalisme” dan “radikalisme”, dua kata yang kemudian dijodohkan dengan istilah “terorisme”.
Istilah fundamentalisme dan radikalisme Islam sebenarnya stereotype yang diciptakan Barat untuk menunjuk kalangan umat Islam yang berusaha kaaffah menjalankan agamanya. Berpegang pada al-Qur’an dan Sunnah, serta tidak “nurut” dan susah diajak berkompromi dengan mereka, yang pada akhirnya kemudian dikesankan reaktif, emosional dan tidak toleran.
Kini, opini publik sedikit demi sedkit mulai dipaksa untuk mengasosiasikan radikalisme maupun terorisme kepada seorang ulama besar yang menyandang gelar Syaikhul Islam; Ibnu Taimiyyah al-Dimasyqi rahimahullah. Meski sebenarnya, hal ini bukan hal yang baru memang. Sekadar menyebut contoh, Andrian Morgan, seorang penulis asal Inggris, pernah mengatakan Ibn Taimiyyah sebagai the real godfather of Islamic fundamentalism yang memberi inspirasi bagi tokoh-tokoh pembaruan yang datang sesudahnya seperti Muhammad ibn Abdul Wahab, Sayyid Qutb dan Abul A’la al-Maududi yang juga disebutnya sebagai ekstremis. Hampir senada, Monte Palmer dan Princess Palmer, penulis buku At the Heart of Terror: Islam, Jihadist and America’s War on Terrorism (terbit tahun 2007), menyebutkan bahwa hampir semua akar gerakan ekstrimisme Muslim modern dapat dilacak jejaknya pada pemikiran Ibn Taimiyyah.
Tuduhan ini tentu perlu diluruskan. Toh, jika seandainya benar bahwa para pelaku terorisme yang muncul belakangan disebut sebut sebagai pembaca buku-buku Ibn Taimiyyah dan sering mengutip fatwa-fatwanya, tidak lantas menjadi absah untuk menyimpulkan bahwa Ibn Taimiyyah adalah sumber ideology of terror. Secara metodologis cara berpikir seperti itu layak dipertanyakan, terlebih lagi jika kemudian mengabaikan faktor politik dan sosiologis yang menjadi variabel utama munculnya terorisme.
Sosok Ibn Taimiyyah, jika referensi karya-karya beliau ditengok secara lebih baik, akan diketahui bagaimana kehati-hatian ulama yang banyak dipuji baik oleh kawan maupun lawannya ini dalam mengkafirkan sesama Muslim. Bahkan selain terkenal dengan keteguhan dalam mempertahankan prinsip dan ghirahnya yang meluap terhadap Islam, Ibn Taimiyyah juga diketahui sebagai sosok pribadi yang lembut, rendah hati, toleran dan lebar dada. Dalam berbagai kasus yang menimpanya, oleh sejarah dibuktikan bahwa Ibn Taimiyyah merupakan seorang ulama mujahid yang pemaaf dan bukan tipe pendendam terhadap musuh-musuh yang menzaliminya, persis seperti perkataan Ibn Taimiyyah sendiri dalam salah satu fatwanya, “Aku telah melapangkan dadaku bagi siapapun yang berselisih denganku. Biarlah! Jika dia melanggar batasan-batasan Allah dengan mengkafirkanku, menyatakan diriku fasik, atau membuat kedustaan dan berlaku fanatik buta, maka aku tidak akan melanggar aturan-aturan Allah terhadapnya.” (Majmu’ al-Fatâwâ:3/245).
Pada kesempatan lain beliau juga menyatakan, “. . .sesungguhnya aku telah menghalalkan/merelakan (kesalahan) setiap Muslim (terhadapku), aku menghendaki kebaikan bagi setiap orang Islam, aku juga mencintai kebaikan. bagi saudaraku sebagaimana aku mencintainyn untuk diriku sendiri, Dan bagi orang-orang yang telah melakukan kebohongan serta aniaya terhadapku, aku telah maafkannya.” (Majmu’ al-Fatawa: 28/55).
Kelembutan hati Ibn Taimiyyah ternyata juga tidak terbatas kepada saudara-saudaranya yang seagama. Suatu ketika, beliau melakukan kesepakatan dengan pemimpin pasukan Mongol untuk melepaskan tahanan yang ditangkap di Baitul Maqdis. Pemimpin Mongol waktu itu bersedia melepaskan para tahanan kecuali mereka yang bukan Muslim, karena dianggap tidak termasuk dalam kesepakatan. Mengetahui hal ini Ibn Taimiyyah pun menolak untuk menyetujui tindakan itu dan menuntut pembebasan mereka semua tanpa kecuali seraya mengatakan kepadanya, “Hendaknya kau bebaskan semuanya termasuk mereka yang berasal dan kalangan Yahudi dan Nasrani, karena mereka adalah juga dalam perlindungan (ahli dzimmah) kami”
Sifat-sifat luhur Ibn Tairniyyah yang toleran dan pemaaf, yang dilupakan oleh kebanyakan orang ini telah dikumpulkan dalam sebuah buku berjudul Ibn Taimiyvah wa al-Akhar (Ibnu Taimiyyah dan Orang Lain) oleh Syaikh ‘Aidh ibn Sa’ad al-Dosari dan diterbitkan di Doha, Qatar tahun 2007. Lantas siapakah dan bagai manakah sebenarnya figur seorang Ibn Taimiyyah?
Biografi Singkat dan Perjuangannya
Ibn Taimiyyah merupakan seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang telah menghabiskan waktunya untuk membela Islam, mengajarkan ilmu, berjihad dan berijtihad. Wawasan keilmuannya sangat luas mencakup berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadits, fiqih, teologi bahkan juga filsafat dan tasawuf. Tak heran warisan buku-bukunya sangat berlimpah dan konon menurut catatan para muridnya mencapai 300 sampai 500 judul buku.
Beliau memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu al-’Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullâh ibn Abul Qasim Al-Khidr ibn Muhamad ibn Taimiyyah. Dilahirkan pada tanggal 10 Rabi’ul Awwal 661H/1263M di Haram, kini propinsi Sanliurfa di tenggara Turki, dekat dengan perbatasan Syria. Akibat serangan Mongol ke wilayah itu, Ibn Taimiyyah kecil harus mengungsi bersama keluarganya ke Damaskus saat berusia tujuh tahun.
Ibn Taimiyyah lahir dan tumbuh di tengah kondisi umat Islam yang carut marut dan mengalami kemunduran baik secara politis, sosial, keilmuan maupun keagamaan. Sekitar lima tahun sebelum beliau dilahirkan, tepatnya Januari 1258, Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah jatuh ke tangan bangsa Mongol. Pasukan Salib yang datang dan daratan Eropa juga telah menguasai sejumlah wilayah umat Islam. Kaum Muslimin sendiri pada masa itu secara umum mengalami keterbelakangan, banyak meninggalkan ajaran agama yang benar atau mencampur adukkannya dengan berbagai unsur yang terinfiltrasi dan luar Islam, serta diwarnai fanatisme buta.
Namun dalam sebuah keluarga yang taat menjalankan ajaran agama dan memiliki tradisi keilmuan sangat kuat, Ibn Taimiyyah telah berhasil membentuk karakternya yang mulia dan intelektualitasnya yang mengagumkan. Kakeknya, Abu al-Barakat Majduddin ibn Taimiyyah merupakan seorang ulama dalam fiqih Hambali yang diperhitungkan. Salah satu karyanya, kumpulan hadits-hadits hukum Muntaqa’ al Akhbâr, kemudian menjadi terkenal bersama syarah (penjelasan) nya Nail al-Authar yang ditulis oleh ‘Ali Al-Syaukâni. Ayah Ibn Tai miyyah sendiri, Syaikh Abdul Halim Syihabuddin merupakan seorang pengajar di Masjid Umayyah Damaskus sekaligus “direktur” di sekolah Dar al-Hadits al Sukkariyah.
Semenjak kecil Taqiyudin Ibn Taimiyyah dikenal sangat cerdas dan telah rnampu menghapal al-Qur’an saat masih berusia sangat muda. Sebelum berusia 20 tahun, beliau sudah rnendapat otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Sepeninggal ayahnya, menginjak usianya yang ke-21, Ibn Taimiyyah menggantikan sang ayah mengajar ilmu Hadits dan Fiqih di Darul Hadits al-Sukkâriyah dan setahun kemudian mulai mengajar ilmu tafsir di Masjid Agung Umayyah. Pada akhir tahun 691 /November 1292, Ibn Taimiyyah pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji dan kembali ke Damaskus tahun 692/Februari 1293.
Karena pembelaan dan kecintaannya kepada Islam, riwayat hidup Ibn Taimiyyah dijalani penuh perjuangan, jihad, fitnah, dan tekanan. Pada tahun 693/ 1293, Ibn Taimiyyah dijebloskan ke penjara untuk pertama kalinya karena sikap dan fatwanya yang cukup keras terhadap seorang Nasrani bernama ‘Assâf yang telah menghina dan melecehkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena kedekatan Assâf dengan kalangan keluarga penguasa, pembelaannya terhadap Rasulullah tersebut justru meghantarkannya ke penjara. Di dalam penjara itulah Ibn Taimiyyah menulis salah bukunya yang terkenal, Al-Shârim al-Masilil ‘ala Syâtim al Rasul (Pedang Terhunus untuk Penghina Rasul).
Menurut sejarah, sepanjang hayatnya Ibn Taimiyyah pernah dipenjara sebanyak tujuh kali, tiga kali diantaranya di Damaskus, Syria dan selebihnya di Mesir (Kairo rnaupun Alexandria). Hampir semua kasus yang mengakibatkannya dijebloskan ke penjara, adalah keteguhannya memegang prinsip kebenaran serta karena kedengkian dan makar para musuh polemiknya yang didukung oleh penguasa. Tetapi Ibn Taimiyyah menjalani cobaan itu semua dengan jiwa besar dan ketegaran luar biasa. Sebagaimana banyak dinukil para penulis biografi beliau, Ibn Taimiyyah senantiasa menyatakan, “Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Surga (ketenangan dan kedamaian)-ku berada dalam dadaku dan akan terus bersamaku tak terpisahkan kemanapun aku melangkah. Bagiku, penjara adalah tempatku untuk menyendiri dan berkontemplasi. Jika aku dibunuh maka itu adalah syahadah dan jika aku diasingkan maka itu adalah kesempatan bagiku untuk melakukan perjalanan jauh.”
Tentang filosofi penjara ini, sebagaimana dinukil oleh muridnya Ibn Al-Qayyim dalam Al Wabil al-Shayyib, Ibn Taimiyyah mengatakan, “Seseorang yang sesungguhnya terpenjara adalah dia yang hatinya terpenjara dan Allah serta keinginannya diperbudak oleh hawa nafsunya.”
Ibn Taimiyyah juga banyak mengisi hidupnya dengan jihad, baik dengan ilmu (bil lisan wa al qalam) maupun terjun langsung ke medan tempur. Selama masa masa invasi tentara Mongol ke Damaskus antara tahun 1299 sampai 1303 M, Ibn Taimiyyah terus menerus mengobarkan semangat jihad di dada kaum Muslimin dengan fatwa-fatwa dan ceramahnya. Pada masa kekuasaan Sultan Al Malik al Mansur Lâjin (696-698/1297- 1299) beliau ditunjuk oleh Sultan untuk ikut serta sekaligus sebagai pembina moral dan pengobar semangat keimanan pasukan jihad yang dikirim dalam perang melawan pasukan Kerajaan Armenia Kecil.
Ibn Taimiyyah juga pernah menjadi jurubicara delegasi para ulama yang datang menghadap pemimpin pasukan Mongol II Khan Ghazan untuk menyampaikan penolakan kehadiran mereka di Damaskus. Bulan Ramadhan tahun 702 H/ 1303 M, dalam sebuah invasi pasukan Mongol, Ibn Taimiyyah ikut berperang dalam pertempuran yang dikenal dengan Perang Syaqhab, beliau saat itu memfatwakan dibolehkannya berbuka selama perang berkecamuk.
Di luar masa-masa perang dan waktu dipenjara, Ibn Taimiyyah memanfaatkan usianya untuk menulis buku-buku dan mengajarkan ilmunya, serta mencetak kader-kader yang kemudian menjadi ulama kenamaan seperti Ibn Qayyim al-Jauziyah (w.1350), Al-Hafidz al Dzahabi (w. 1348) dan Ibn Katsir (w. 1372).
Pembaruan dan Pemikiran Ibn Taimiyyah
Ibn Taimiyyah sangat menaruh perhatian dan keprihatinan sangat besar terhadap kondisi umat Islam saat itu. Dengan menggunakan timbangan naql (wahyu) dan akal, serta teladan salaf al-salih beliau menyimpulkan bahwa umat Islam telah menyimpang dan karakter aslinya, sehingga mengalami kemunduran, keterbelakangan dan tunduk kepada bangsa lain. Dan situ beliau memulai proyek pembaruannya yang komprehensif dengan mencontoh prinsip Imam Malik ibn Anas (w. 179 H/ 795M) bahwa, “Generasi umat Islam masa kini tidak akan pernah berhasil dan menjadi unggul kecuali dengan apa yang menjadikan generasi pertama umat Islam menjadi berhasil dan unggul.”
Menyadari sentralitas konsep Tauhid dalam sistem bangunan Islam, Ibn Taimiyyah mengerahkan upaya terbesarnya untuk memurnikan akidah Islam dan kesyirikan dan infiltrasi berbagai unsur luar seperti filsafat Hellenis-Yunani, mistisisme, paham hulul (inkarnasi), wahdat al-Wujud (pantheisme monisme) dan fatalisme (jabariyah).
Ibn Taimiyyah berupaya kuat untuk membangun kembali hubungan antara realitas dan problem umat dengan sumber sumber Islam yang murni, serta membangun kesadaran tugas hidup manusia dan misinya di dunia dengan jihad dan ijtihad (menggunakan akal sehatnya secara benar dan optimal). Maka dan itu, meski Ibn Taimiyyah sangat ketat berpegang kepada Al-Qur’an dan Sunnah, beliau juga menggunakan qiyas (analogical reasoning) dan argumentasi kemaslahatan (al-mashlahah) dalam pemikirannya. Menurut beliau, hanya dengan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnahlah kaum Muslimin dapat kembali bersatu dan tidak terpecah belah.
Dalam masalah ibadah, Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa manusia tidak membutuhkan perantara untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Beliau juga berjuang keras untuk membersihkan cara-cara beragama yang dipenuhi dengan bid’ah. Seorang Muslim menurutnya tidak harus tunduk kepada satu madzhab dan pendapat golongan tertentu, jika didapati bertentangan dengan teks-teks otentik dan al-Qur’an maupun Sunnah.
Dalam masalah politik, Ibn Taimiyyah meyakini bahwa membangun negara adalah bagian dan perintah Allah. Melalui negara, doktrin al-amru bi al-ma’ruf dan al nahyu ‘an al-munkar dapat diwujudkan dengan semestinya. Negara juga merupakan amanah untuk menyelesaikan urusan urusan masyarakat banyak.
Ibn Taimiyyah, dengan segala kekurangan dan kelemahannya, nyatanya merupakan tokoh besar yang patut dibanggakan umat Islam. Ibn Hajar al-’Asqallani (w. 852/1448), seorang ahli hadits terkemuka, dalam salah satu pernyataannya pernah memuji Ibn Taimiyyah, “Pengakuan akan keimaman (ketokohan) Taqiyuddin (ibn Taimiyyah) lebih terang dan pada matahari. Gelaran Syaikh al-Islam pada zamannya masih terus lestari hingga sekarang di atas lidah-lidah yang berbudi luhur dan akan lestari hingga hari esok sebagaimana hari kemarin. Tidaklah seorang pun mengingkarinya kecuali mereka yang tidak mengerti atau berpaling dan sikap adil…”
*Alumnus Kulliyah al-Dakwah al-Islamiyah Tripoli, Libya Mahasiswa Pasca Sarjana
Pendidikan dan Pemikiran Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor
Sumber: Majalah Sabili, No. 6 TH. XVII 19 Syawal 1430